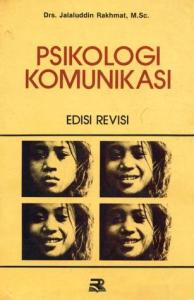Apakah Anda percaya jika saya katakan bahwa manusia itu rentan sekali penasaran, alias ingin tahu tapi agak akut. Ya ingin tahu saja, tidak ada kelanjutannya. Boleh, kan?
Rasa ingin tahu agak akut itulah yang menjangkiti benak saya suatu hari. Suddenly begitu saja. Ketika sedang mengumpulkan kesadaran yang tercerai berai karena tidur, di sebuah siang pada hari libur.
Rasa itu kemudian mendorong saya untuk keluar rumah. Melongok ke luar pagar dan menolehkan kepala ke kanan. Ke arah rumah tetangga yang berdempet dengan rumah saya.
Sebagai single yang hanya mampu membeli rumah di kompleks perumahan bukan mewah, saya tinggal tak berjarak dengan tetangga. Berdempet dengan satu tetangga. Samping kiri taman.
Rumah sebelah sepi-sepi saja. Tapi saya tahu, ada perempuan muda yang baru saja sebulan menikah di rumah itu. Suaminya bekerja sebagai marketing di sebuah bank swasta nasional.
Si suami sudah menjadi tetangga saya setahun terakhir. Dia sibuk, saya menyibukkan diri. Tak pernah benar-benar dekat meski rumah berdempet sekali.
Si istri masih sangat muda, untuk ukuran umur saya yang sudah kepala tiga. Saya taksir usianya baru duapuluhan awal. Mungkin baru lulus kuliah. Tiga pekan lalu saat baru datang, si istri bertamu di sekitar rumah, bermaksud berkenalan.
Namanya Vita. Tiga minggu berselang setelah perkenalan itu, saya nyaris tak pernah bertemu lagi dengannya. Hanya sekali ketika di swalayan depan kompleks. Saya beli kopi, dia belanja banyak sekali.
”Mbak Fika…belanja juga?” celetuknya membuat saya sedikit bingung dan kaget ditambah berpikir agak lama mengingat, siapa dan pernah bertemu dimana. Maklum saya pelupa akut.
”Oh eh hai…ini beli kopi,” kata saya kemudian mendapat giliran membayar lebih dulu di kasir. ”Duluan ya…harus ke kantor nih.”
Dia tersenyum mengangguk. Di perjalanan saya baru bisa ingat dia adalah tetangga sebelah rumah dan bernama Vita. Payah betul saya ini. Mungkin memang perlu periksa otak.
Setelah itu saya sibuk berkutat dengan hidup saya sendiri. Di kompleks ini, saya mungkin termasuk warga yang paling asosial. Jarang bergaul. Terlebih dengan nyonya-nyonya kompleks. Mungkin banyak yang sebaya, tapi kehidupan saya tetap tidak bisa nyambung dengan mereka.
Status saya yang menjadi pembeda. Menjadi single, tanpa suami dan anak, membuat obrolan antara saya dan mereka tak bisa sejalan. Selain juga saya sangat sok sibuk dengan pekerjaan.
Baru ingat lagi soal Vita, ya sekarang ini. Sedang apa ya dia siang-siang begini. Suaminya pasti sedang bekerja. Dia begitu cantik seperti tuan puteri. Selain belanja ke swalayan, apa iya dia sering rumpi sana sini dengan nyonya-nyonya kompleks?
Setahu saya hampir semua nyonya di kompleks ini adalah perempuan pekerja. Arisan nyonya-nyonya kompleks memang ada, tapi itu sebulan sekali. Acara rumpi ringan juga ada tapi itu pagi-pagi sekali, sebelum mereka mandi dan berangkat bekerja bareng suami atau anak-anak ke sekolah.
Ini tengah hari, tak ada acara rumpi. Tak ada agenda arisan. Tuan puteri tentu sendirian. Sama seperti saya sekarang. Tapi saya terbiasa sendiri, sebentar lagi saya juga duduk di depan komputer, mengetik. Sementara dia?
Apa dia juga senang mengetik sesuatu yang tak jelas seperti saya? Menjadi pengkhayal berat di siang bolong mirip saya juga? Atau dia sedang memasak? Menyiapkan candle light dinner untuk si suami?
Pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah ada jawabannya. Tentu saja, saya bertanya pada diri sendiri yang tidak tahu apapun. Jelas tidak ada jawabannya. Saya lantas terusik.
Haruskah saya pura-pura main ke rumah sebelah? Sekadar tersenyum garing dan basa-basi, hai tuan puteri sedang apa siang-siang begini?
Ah konyol sekali. Tapi saya penasaran. Harus apa saya untuk menuntaskannya kecuali main ke sebelah? Melihat langsung si pemicu rasa penasaran itu. Barangkali bisa tuntas lalu saya kembali ke rutinitas, minum kopi sambil mencari inspirasi.
Heran sekali, kenapa bisa penasaran seperti ini. Apa sih pentingnya tahu istri orang sedang apa siang-siang begini? Tak penting sekali. Lantas tiba-tiba sehabis mandi, saya sudah di depan pintu rumah sebelah, tangan kanan memencet bel. Bercelana pendek, dan berkaos oblong bergambar tujuh kurcaci mengelilingi Puteri Salju.
Ah kebetulan sekali, saya juga sedang mendatangi seorang puteri, istri pangeran tetangga sebelah. Apa yang harus saya katakan nanti jika pintu terbuka, selamat siang tuan puteri…hamba penasaran ingin tahu tuan puteri sedang apa?
Tapi bayangan puteri cantik segera lenyap. Menyembul dari balik pintu seorang perempuan bermata sembap. Jelas sekali sehabis menangis. Saya yang terlanjur menyiapkan senyum garing dan basa-basi yang basi, kaget.
“Oh Mbak Fika, ada apa ya?” tanyanya to the point.
“Oh nggak ada apa-apa kok, hanya ingin main. Bolehkan?”
***
Setelah dipersilakan duduk saya nyerocos, basa basi tapi sebenarnya memiliki tujuan pasti, menuntaskan penasaran yang menggelitik sejak tadi.
“Kebetulan hari ini saya libur, ya tidak benar-benar libur sih, masih banyak tulisan juga. Tapi secara hitungan absensi kantor, saya libur.” Ini ngomong apa sih saya juga bingung. Buat apa juga menjelaskan pada tuan puteri bermata sembap ini kalau saya libur, tapi tidak benar-benar libur.
Vita, si tuan puteri bermata sembab itu hanya senyum. Sikapnya yang dingin malah membikin saya kikuk. Membuat basa-basi saya tambah basi. Bingung harus bicara apalagi.
“Saya nggak pernah masuk rumah ini, ini pertamakalinya,” ujar saya makin ngawur. Tapi malah membuat si tuan puteri bersuara.
“Oh ya? Mbak Fika kan sudah bertetangga cukup lama dengan Mas Dwi, kok bisa nggak pernah main ke sini? Sibuk ya?” Saya gantian yang senyum. Tuan puteri sudah berubah mood.
“Ya itu karena kami sama-sama sibuk. Aneh ya? Tapi zaman sekarang model tetanggaan seperti saya dan Mas Dwi itu banyak.”
Obrolan disambung dengan suguhan air dingin, dan keripik kentang. Si tuan puteri lantas bercerita mereka menikah mendadak. Dijodohkan. Di kampung, orangtua mereka bertetangga dekat.
Saya hanya ah oh saja mendengarkan. Lalu membumbui cerita itu dengan mengatakan, tetangga sekitar juga agak kaget, tiba-tiba Dwi pulang kampung di Yogya, lalu ketika kembali sudah membawa istri.
“Yang tidak kaget ya hanya Pak RT dan Bu RT yang dilapori Mas Dwi,” kata saya.
“Saya ini sebenarnya takut mbak. Saya belum terlalu kenal Mas Dwi. Di rumah ini saya juga sepi, tidak punya teman kalau siang. Ingin main ke tetangga juga bingung, banyak yang kerja,” nadanya sedih.
Waduh, saya tambah bingung. “Tapi kan ada internet, kamu bisa browsing. Beli buku, atau majalah. Bisa nonton TV. Saya malah menyangka tadi kamu sedang memasak,” ini dia saatnya mengorek keterangan si tuan puteri sedang apa siang-siang begini.
“Iya sih, saya tadi memang sedang memasak. Tapi saya lantas sedih, ingat ibu di kampung, hanya berdua adik lelaki saya. Saya kangen.”
Waduh, kata saya dalam hati. Bisa-bisa waduh-waduh terus mendengar ceritanya. Seperti penasaran tadi, suddenly saya jatuh kasihan pada Vita. Di kota ini, perempuan seumur Vita masih senang-senangnya bebas.
Saya membandingkan dengan diri sendiri. Ketika lulus kuliah, dan tak langsung bekerja, saya bermain sepuas hati. Belajar lagi banyak hal. Ikut kursus sana-sini. Dan ketika mendapat pekerjaan di dunia yang saya inginkan, saya eksplorasi diri sepuas hati. Toh tak ada yang membebani, semacam anak atau suami.
Ketika melihat Vita, rasa kasihan muncul. Barangkali karena saya berpikir, tak seharusnya dia ‘terjebak’ pernikahan model konvensional begini di usia yang masih dini menurut ukuran saya.
Barangkali ceritanya akan lain, jika Vita memutuskan ingin menikah sendiri. Setidaknya dia lebih siap menghadapi konsekuensi yang dipilihnya. Bukan karena desakan orangtua.
Aneh juga, zaman semodern ini, secanggih ini, masih ada agenda jodoh-jodohan. Saya terus terang, tidak tahu bisa membantu apa. Atas rasa kasihan terhadap Vita, saya hanya bisa diam. Ketika sore turun, saya pamit.
Rasa penasaran saya hilang, berganti dengan kasihan sembari tak tahu apa yang harus saya lakukan untuk bisa membantunya. Saya, selain hari libur begini, hampir tak pernah punya waktu.
Dan setelah hari itu, lama sekali saya tidak pernah lagi berbincang panjang dengan Vita. Hanya say hello ala kadarnya ketika berpapasan. Persis dengan tatacara saya bertetangga selama ini. Kesibukan memang memenjara, bahkan dari sekadar tetangga.
***
Saya tidak ingat, sudah berapa pekan lewat sejak iseng main ke rumah sebelah. Di kompleks ini, kehidupan berjalan baik-baik saja. Setidaknya begitu di mata saya. Mungkin karena saya asosial, tapi semoga memang baik-baik saja seperti kelihatannya. Juga tetangga sebelah yang istrinya kesepian tiap siang hingga hampir malam.
Saya tak pernah mendengar mereka cekcok. Hingga sampailah pada suatu subuh, di hari pertama saya cuti setelah berpekan-pekan terjerat kerja. Saya bertemu Dwi, suami Vita. Wajahnya kusut, matanya merah, sembab.
“Dwi, baru pulang? Tumben. Lembur?” saya basa-basi karena melihatnya memarkir mobil.
“Tidak Fik, dari rumah sakit,” katanya menghampiri saya.
“Siapa yang sakit?” dalam benak saya menebak, pasti istrinya.
“Vita, keguguran,” jawabnya pendek. Lantas malah duduk di teras rumah saya. Bahasa tubuhnya menunjukkan dia ingin berbagi cerita.
“Terus, Vita sama siapa sekarang? Kok malah kamu tinggal pulang?” nada pertanyaan saya khawatir sungguhan, bukan dibuat-buat sekadar berpura-pura simpati.
“Ada ibunya dan ibu saya, semalam datang dari Yogya.”
Subuh itu, saya batal menghirup oksigen segar sambil lari pagi. Saya malah melihat lelaki menangis. Dwi bercerita, Vita sengaja minum jamu untuk mengugurkan kandungannya dan lompat-lompat di kamar mandi rumah mereka.
Vita yang juga pendiam itu tak pernah bercerita, bahwa sebenarnya dia sangat takut menjalani rumah tangga. Ketakutan yang sebenarnya wajar jika bisa dibagi dengan orang lain. Sayangnya orang lain itu tidak ada. Dwi, juga para tetangga sibuk dengan urusan mereka.
Sesaat setelah sadar dari proses kuret, Vita menangis dan mengatakan belum ingin punya anak. Dia masih ingin belajar banyak, meski telah jadi istri.
“Saya tak pernah tahu Fik, dia tak pernah bilang. Saya pikir semuanya baik-baik saja. Dia istri yang baik,” Dwi menghapus setitik airmata dengan jari telunjuknya.
Saya juga kepingin menangis, dan tiba-tiba merasa sangat egois. Selama ini saya hidup sendiri, bersenang-senang sendiri. Sedangkan di rumah yang berdempet dengan tempat tinggal saya, ada perempuan yang butuh teman. Sekadar teman.
Egois sekali saya jadi manusia, hanya berbagi sedikit cerita saja saya tak mampu. Hanya meluangkan 10 menit waktu saja saya tak bisa.
Apakah kerja telah menjadi segala-galanya yang terbaik bagi saya? Saya sungguh kepingin menangis dan merasa ironis. Setelah ini Vita, saya ingin tak sekadar menjadi tetangga, tapi juga sahabat berbagi rasa. Saya janji dalam hati. Siangnya saya sudah semobil bersama Dwi, meluncur ke rumah sakit. Menengok Vita.
-May Hera-
Jogja, Desember 2010
Cerita ini pernah dipublikasikan di Majalah Chic edisi Februari 2011